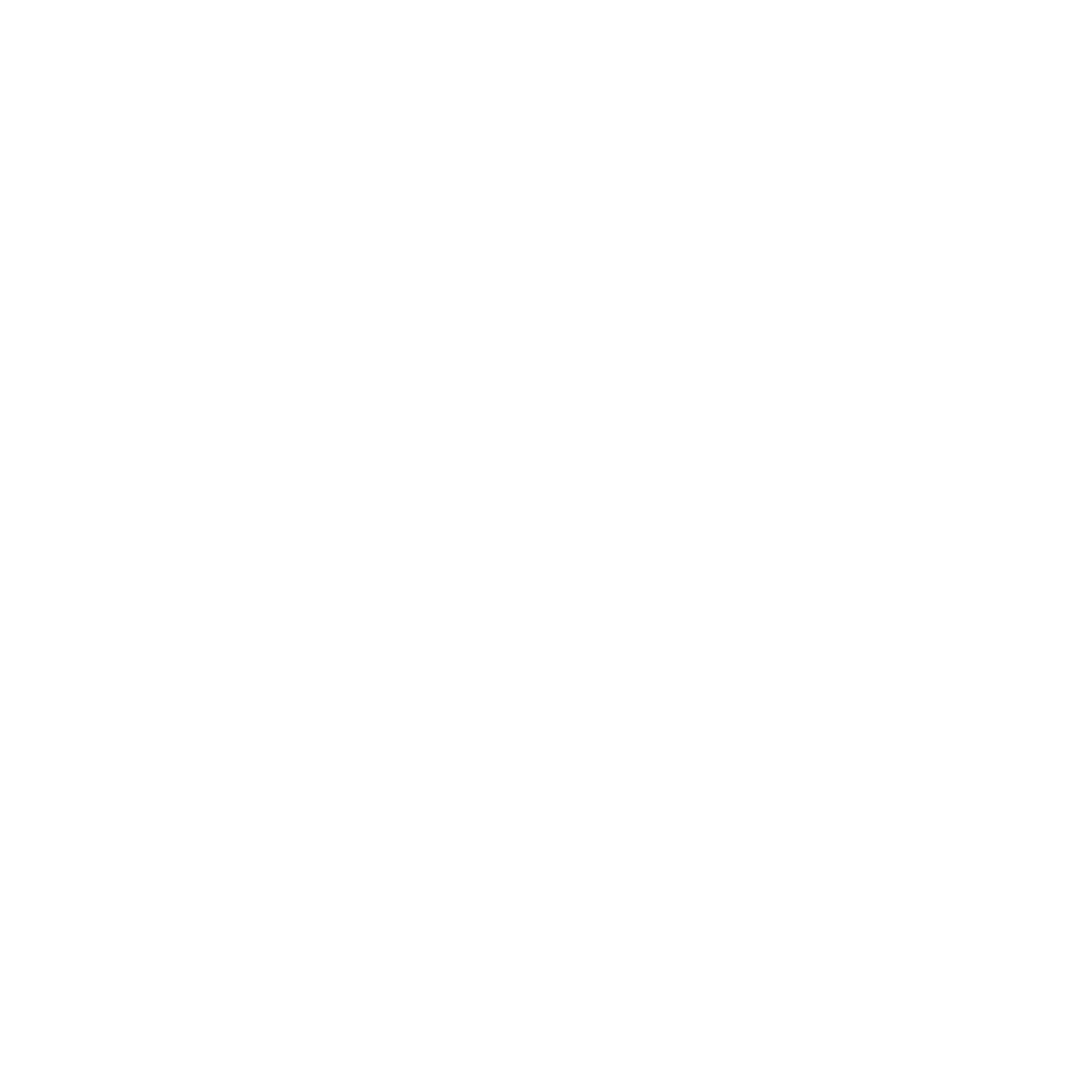Sejak adanya pandemi COVID-19, Bu Neni[i] yang sehari-hari berjualan makanan dan membuka warung di depan rumahnya lebih banyak mengisi waktunya dengan mengurus cucunya di rumah. Lebih-lebih sekolah cucunya diliburkan akibat pandemi, jadi baik Bu Neni dan cucunya tidak pernah keluar rumah.
"Saya tidak pernah ke mana-mana. Saya di rumah aja," adalah pernyataan yang berkali-kali disampaikan kepada kami dalam wawancara pada Sabtu siang itu. Berjualan keripik yang baru dilakoninya selama sebulan terakhir juga dilakukan secara daring; pembelinya pun kebanyakan adalah tetangga dekat rumah.
“Saya takut dengan risiko sanksi adat dan takut risiko kena corona kalau saya keluar-keluar rumah,” ujar Bu Neni.
Bu Neni bukanlah satu-satunya warga yang mengaku berkomitmen menerapkan pembatasan fisik di tempat tinggalnya, yaitu Desa D. Di sana pembatasan fisik telah melebur ke dalam peraturan adat. Di desa yang berlokasi di Kabupaten Badung, Provinsi Bali tersebut, kepatuhan warga terbentuk atas kesadaran akan dua risiko: risiko terinfeksi COVID-19 dan risiko menanggung malu karena mendapat sanksi adat jika melanggar peraturan.
“Sanksinya ya diceramahi berjam-jam oleh petugas desa adat, disaksikan oleh tetangga-tetangga. Jadi ya malu,” kata Bu Neni.
Menurut pacalang[ii] desa tersebut, sanksi adat berhasil membuat hampir 90% warga patuh pada imbauan pembatasan fisik dan kegiatan sosial yang menimbulkan kerumunan. Terkesan ada rasa bangga dari pacalang Desa Adat D ketika menceritakan perilaku warganya tersebut. Pengawasan yang ketat dari para aparat desa adat, yang kemudian menjalar ke pengawasan antartetangga, menciptakan kepatuhan warga pada anjuran protokol kesehatan semasa pandemi.
Provinsi Bali memang bukan termasuk episentrum penyebaran COVID-19, tetapi provinsi ini sempat mengalami lonjakan-lonjakan kasus positif COVID-19 yang terutama bersumber dari pekerja migran Indonesia (PMI).
Desa D sendiri sempat mengisolasi tiga warganya yang terinfeksi COVID-19. Mereka semua pekerja migran yang baru pulang ke desa. Keberadaan ketiga pasien tersebut membuat aparat desa bekerja lebih keras untuk mengamankan desa dan warganya.
“Syukur semua sekarang sudah sembuh dan desa kami bebas dari COVID-19. Namun demikian, kami tetap berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memantau perkembangan dan situasi dari pulangnya para pekerja migran ke kampung kami,” ujar kepala desa Desa D.
Bali memang terkenal dengan pranata sosial budaya yang bersumber dari adat. Pranata tersebut berakar dari ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
Pranata adat serta faktor sosial-budaya berperan besar dalam membentuk persepsi risiko di masyarakat. Di tengah pandemi, persepsi risiko yang tinggi ini membentuk kepatuhan di masyarakat Bali.
Kepatuhan akan protokol kesehatan semasa pandemi juga kami temukan pada saat mewawancarai Bu Eni yang baru saja kembali ke desanya di Purbalingga.
“Rata-rata warga di sini pada patuh [pada anjuran kesehatan]. Pada pake masker. Yang pulang dari Jakarta harus melapor ke desa, dicek suhu [tubuhnya], lalu dikasih gelang buat tanda kalau baru datang. Saya juga pas pulang gak ke mana-mana. Di rumah aja,” ujar Bu Eni.
Walaupun tidak ada sanksi adat, seperti di Desa D, warga desa tempat tinggal Bu Eni mematuhi instruksi para aparat desa. Melihat bahwa setidaknya ada satu orang dari setiap keluarga yang bekerja di luar desa, seperti di Jakarta, penduduk desa ini sebenarnya memiliki risiko yang tinggi tertular COVID-19. Untunglah sampai saat wawancara dilakukan, yaitu pada awal Juni 2020, hal tersebut tidak terjadi.
Pemahaman tentang risiko COVID-19 dan tingkat kepatuhan warga di Bali dan Purbalingga terasa kontras ketika kami mendengarkan penuturan beberapa warga yang bermukim di salah satu perkampungan padat di Kelurahan C, Jakarta Timur. Bisa dikatakan bahwa pemahaman warga kampung tersebut tentang risiko terinfeksi COVID-19 sangat bervariasi, bahkan cenderung rendah.
"Kalau diperhatikan, perbandingannya adalah 40% dan 60% [mayoritas tidak paham]. Lebih banyak warga yang tidak pakai masker dan tidak menjaga jarak, [dan] masih sering kumpul-kumpul dengan tetangganya," tutur Wardi yang sudah bermukim di kampung ini selama lebih dari sepuluh tahun.
Menurut Wardi, banyak warga yang beranggapan, “Ah sama tetangga sendiri juga kumpulnya. Saya sehat, dia juga keliatannya sehat, jadi ya nggak apa-apa.”
Hasil pengamatan lebih lanjut informan kami terhadap kondisi sosial-ekonomi di kampung tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memengaruhi pemahaman warga tentang faktor risiko.
“Ya bukan apa-apa, tapi warga di sini umumnya tingkat pendidikannya masih rendah, jadi kurang paham,” ujar Wardi.
Walaupun sudah ada upaya lebih dari pihak pengurus rukun tetangga (RT) dalam mengimbau dan meningkatkan kesadaran warga akan risiko COVID-19 dan potensi penularannya, pada praktiknya sulit untuk menjamin kepatuhan warga pada imbauan tersebut.
“Kalau Pak RT termasuk yang aktif, suka bertanya juga ke warga kalau dapat informasi. Misalnya, tanya ke saya, ini hoax atau bukan, sebelum kasih tahu ke warga lainnya,” tutur Wardi.
“Peringatan sih ada, Bu, kalau ada yang kumpul-kumpul, atau keluar gak pakai masker. Biasanya Bu RT yang paling sering mengingatkan. Tapi ya susah juga. [Patuh tidaknya] Tergantung orangnya,” tambahnya.
Di lain pihak, pertimbangan mengenai risiko COVID-19, termasuk risiko terinfeksi COVID-19, juga dipengaruhi oleh fakta seberapa dekat penyakit tersebut dengan diri kita. Hal ini tecermin dari perilaku warga Kelurahan A, salah satu permukiman kelas menengah di pinggir kota Jakarta Timur. Terinfeksinya warga salah satu RT di kelurahan itu ternyata memancing reaksi dan respons yang cukup kuat.
RT sebelah menutup jalan dengan portal, menyemprot rumah-rumah dengan disinfektan, dan bahkan mengawasi warga yang keluar-masuk lingkungan dengan ketat.
“Kami sempat khawatir memang,” kata Pak Samsu, ketua rukun warga (RW) setempat.
Di tengah kondisi pemahaman dan respons masyarakat yang berbeda-beda terkait risiko COVID-19, keputusan dan kebijakan dari tingkat pusat sampai tingkat RT yang kerap berubah juga memengaruhi persepsi dan pemahaman masyarakat bukan hanya tentang risiko terinfeksi COVID-19, tetapi juga mengenai risiko ekonomi.
Keinginan untuk menjaga ketenangan di tengah masyarakat dan mencegah kepanikan membuat para pemimpin masyarakat tidak mengomunikasikan informasi tentang risiko COVID-19 dengan semestinya.
Di dalam masyarakat sendiri, pertimbangan yang sering muncul tidak selalu berkaitan dengan COVID-19, bagaimana mengantisipasinya, atau bagaimana menangani warga yang terinfeksi. Di Kelurahan C, misalnya, yang kerap ditanyakan warga adalah,
"Kapan bantuan turun?" "Kapan saya dapat bantuan?"
Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat secara konstan menimbang-nimbang antara risiko kesehatan dan dampak ekonomi dalam keseharian mereka. Pertimbangan tersebut memperlihatkan adanya kontestasi antara pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat dan informasi yang disampaikan oleh pemerintah tentang risiko kesehatan dan risiko ekonomi yang ditimbulkan oleh COVID-19. Hasil pertimbangan tersebut berpengaruh pada pemahaman masyarakat dan tingkat kepatuhan mereka pada protokol kesehatan.
Pelonggaran, Rasa Bosan, dan Ancaman Penularan yang Masih Tinggi
“Anak-anak udah mulai ngaji di RT sebelah. Sebelumnya kan ngajinya memang di sana, tapi karena lockdown jadi gak ngaji dulu. Sekarang udah balik ngaji ke sana. Mana sekarang lagi musim layangan kan, jadinya pada main," tutur Bu Era yang juga tinggal di Kelurahan C, Jakarta Timur.
“Anak saya juga minta berenang. Biasanya tiap ulang tahun Jakarta kan masuk kolam renang gratis, tapi saya belum berani. Ini udah pada bosan juga di rumah,” ia melanjutkan.
Saat ini Jakarta berada dalam fase transisi sejak aturan PSBB berakhir pada 14 Juni 2020. Menjelang berakhirnya PSBB, berbagai lini media massa, termasuk media sosial, dipenuhi dengan panduan beraktivitas di masa transisi ini, yang kerap disebut dengan periode kenormalan baru.
Di Desa D, aktivitas warga disebutkan mengalami peningkatan. Warung-warung makan sudah mulai beroperasi sampai malam seiring dengan berakhirnya masa Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM). Jalan raya di depan desa pun sudah mulai ramai, seperti yang dituturkan oleh Bu Neni.
“Istilahnya, yang tadinya mau duduk atau tiduran di jalan gak ada yang nabrak, sekarang mau nyebrang aja susah,” ujarnya.
Pak Munir, suami Bu Neni, pun sudah mulai lebih sering ke luar rumah. Perusahaan tempatnya bekerja sudah mulai mengontak karyawannya untuk bersiap-siap menghadapi permintaan jasa mereka. Walaupun belum ada pemasukan, dapat kembali beraktivitas membuat suami Ibu Neni kembali bersemangat.
Banyak orang berharap kondisi ekonomi akan kembali ke seperti sebelum pandemi. Bu Neni menunggu-nunggu kapan dia akan bisa membuka warung makannya kembali dengan antrean pembeli yang mengular bahkan sebelum warungnya buka.
Di Kelurahan A, keberadaan portal yang tadinya dimaksudkan untuk memberikan rasa aman, sekarang sudah mulai dirasakan mengganggu. Di tengah harapan akan kembali berlangsungnya aktivitas harian warga, termasuk aktivitas ekonomi, ancaman infeksi dan penyebaran COVID-19 masih tinggi. Jakarta dan Bali, misalnya, masih mengalami peningkatan jumlah kasus harian yang cukup tinggi.
Menghalau Rasa Aman Semu
Sejak kasus pertama COVID-19 diumumkan pemerintah hingga tiga bulan sesudahnya, persepsi masyarakat mengenai risiko COVID-19 berubah-ubah.
Kondisi di empat komunitas di atas menunjukkan bahwa tingkat pemahaman tentang risiko dalam wujud kepatuhan masyarakat tidak bisa lepas dari faktor sosial-budaya, serta faktor respons kebijakan dan penanganan COVID-19.
Mengingat bahwa faktor risiko yang dihadapi tiap orang dan kelompok tidak sama, begitu pula respons kepatuhan masyarakat yang bervariasi, maka mengomunikasikan risiko COVID-19 kepada berbagai kelompok masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi yang ada menjadi sangat penting untuk dilakukan dengan segera.
Tingkat pemahaman masyarakat yang tinggi mengenai risiko COVID-19, termasuk pengetahuan tentang mekanisme transmisi penyakit tersebut, sangat diperlukan untuk menghalau rasa aman semu (false sense of security) yang kerap muncul dalam konteks bencana.
Seperti dipaparkan oleh Montz dan Tobin dalam artikelnya yang diterbitkan dalam jurnal Geografický Časopis, pembangunan tanggul penahan air di pinggir sungai merupakan contoh intervensi mitigasi pengurangan risiko banjir yang menimbulkan rasa aman semu. Keberadaan tanggul tidak benar-benar mengurangi risiko banjir dan malah meningkatkan risiko bagi masyarakat yang tinggal di pinggir sungai ketika tanggul tersebut jebol.
Jika dikaitkan dengan pandemi COVID-19, ketika Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah terburu-buru memperkenalkan kebijakan kenormalan baru kepada masyarakat, masyarakat bisa saja mengira bahwa keadaan sudah jauh membaik sehingga mereka dapat beraktivitas seperti sedia kala. Tanpa diiringi dengan kesiapan masyarakat yang dimulai dari pemahaman yang benar tentang risiko COVID-19, kebijakan tersebut berpotensi menambah jumlah pasien COVID-19 dan merugikan perekonomian dalam jangka panjang.
Melihat bahwa kini jumlah kasus positif COVID-19 bertambah sekitar 1.000 per harinya, bahkan mencapai 2.657 per 9 Juli 2020, kepalsuan rasa aman yang ada terasa makin nyata, bukan?
------------------------------------------------------------------------
[i] Nama-nama responden dalam feature ini disamarkan.
[ii] Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, pacalang adalah satuan tugas keamanan tradisional Bali yang dibentuk oleh desa adat dan bertugas menjaga keamanan dan ketertiban wilayah desa adat. Pacalang juga dapat mengacu pada personal satuan tugas tersebut.